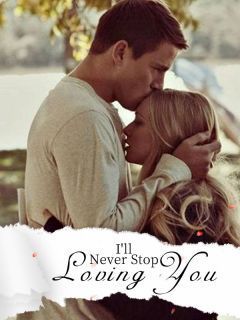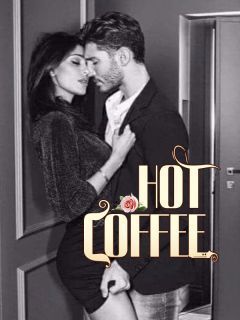Gue ini monster. Bukan berarti orang jahat, gue ke gereja dan bayar pajak, tapi gue nggak bisa proses emosi kayak orang lain. Gue nggak ngerasa bersalah atau menyesal, dan karena nggak ada perasaan itu, semuanya jadi berlebihan. Kalau gue marah, gue ngamuk, dan kalau gue seneng, gue jadi terobsesi. Nggak kayak Frankenstein-nya Shelley sih, tapi nggak cukup manusiawi buat kebanyakan orang.
Kalau kita mau bahas soal bawaan lahir VS didikan, gue yakin bisa nyalahin bokap gue buat semuanya. Dia beneran orang jahat. Setelah ngerayu nyokap gue dari Korea sebagai pengantin pesanan dengan janji-janji akan jadi suami yang penyayang dan suportif, gue rasa dia nggak pernah sehari pun selama pernikahan mereka nggak mukul nyokap gue. Begitu gue udah cukup gede, gue mulai bales mukul dia, dan akhirnya gue dikirim ke sekolah swasta yang mahal dan bergengsi yang dia mampu bayar, apa aja biar gue nggak ganggu. Dia nggak mau bayarin gue buat pulang, jadi gue belajar kerja keras dan cari kesempatan dengan dorongan dan rasa lapar kayak binatang buas. Gue nabung dan mulai investasi dengan bagus dari awal. Seneng banget gue lihat muka kaget dia waktu gue tiba-tiba muncul di depan pintu buat ngehajar mukanya.
Akhirnya, gue lulus dan masuk kampus ternama, tapi nggak sebelum ngeluarin duit buat mastiin bokap gue nggak bakal nyakitin nyokap gue lagi. Gue pengen banget ngelakuinnya sendiri, pelan-pelan dan menyakitkan, tapi gue udah punya pengaruh tertentu di mana kesenangan kayak gitu bakal bahaya buat masa depan gue. Jadi, gue nyuruh profesional yang nanganin. Satu-satunya yang tersisa dari dia cuma matanya, soalnya mata gue sama hijau jahatnya kayak dia.
Gue pindahin nyokap gue dari rumah itu ke kota tempat gue kuliah dan nanya dia mau ngapain sama rumah itu. Gue seneng banget gandengan tangan sama dia di halaman depan waktu kita lihat rumah itu kebakar. Gue yakin dia selalu tau ada yang salah sama gue, tapi dibandingin dia, gue ini malaikatnya. Lebih baik monster yang lo sayang.
Gue lulus Summa Cum Laude di program master. Dengan nyokap gue di kota yang sama, gue bisa jalan terus tanpa masalah. Gue cuma ambil cuti setelah lulus buat ajak dia jalan-jalan ke kampung halamannya, tempat yang udah nggak dia kunjungi lebih dari dua puluh tahun.
Sekarang umur gue 28 tahun, gue kerja sebagai Investor Malaikat. Gue bisa kerja dari rumah, tapi gue punya kantor di pusat kota karena nyokap gue pengen lihat gue kerja di balik meja. Kantor gue makan satu lantai di gedung tinggi cuma buat gue, sekretaris gue, dan ruang santai buat klien.
Gue udah capai banyak hal di usia yang masih muda, jadi gue harus prioritaskan apa yang gue mau selanjutnya. Gue bisa aja keliling dunia, tapi keliling dunia terus-terusan kayaknya nggak ada gunanya. Apa yang bakal gue lihat? Orang-orang dan tanah. Pasti indah, nggak diragukan lagi, tapi orang-orang dan tanah, orang-orang dan tanah. Gue bisa aja jadi relawan di suatu tempat, tapi itu juga nggak ada gunanya, gue cuma bakal jadi orang yang berbuat lebih banyak buat pengalaman gue sendiri daripada buat kebaikan orang lain.
Dan saat itulah, pikiran itu mulai muncul di kepala gue. Awalnya cuma kayak kerlipan, belum berkilau, tapi makin hari makin terang. Mungkin udah waktunya mikirin soal keabadian. Gue nggak lagi ngomongin air mancur awet muda atau hal mistis lainnya, tapi cara kuno. Udah waktunya punya keturunan.
Gue mikirin ide itu cukup lama sampai gue sadar ide itu nggak bakal hilang. Gue bakal punya anak dalam beberapa tahun ke depan. Ini udah bukan pilihan lagi, cuma soal kepastian saat gue mulai menggulirkan bola ke depan. Gue bakal cerita soal perburuan nyari ibu yang sempurna buat anak-anak gue, tapi dia udah kerja buat gue dari dulu.
Sekretaris gue adalah pilihan yang sempurna. Namanya Samantha Logan, panggilannya Sam. Gue nggak bisa bikin cerita kayak gini. Dia tumbuh besar di kota kecil di Selatan Georgia.
Kecil banget, acara paling besar tahunan cuma festival buah persik. Ayahnya pendeta, ibunya guru sekolah. Dia adalah potongan kecil sempurna dari Amerika yang murni. Keseimbangan yang luar biasa buat tingkat k*nt*l yang gue warisi.
Dia cantik. Tinggi, yang buat gue jadi nilai plus, rambut keriting liar yang dia ikat jadi sanggul tinggi, dan kulit sawo matang yang bersinar. Pahanya, ya ampun gue bisa mikirin pahanya yang berisi, pinggulnya yang lebar, dan bokongnya yang montok seharian. Sam itu wanita seutuhnya, bahkan pinggangnya yang mengecil dari pinggulnya masih lembut. Gue cuma pengen ngusap-ngusap dia waktu gue lihat dia bergerak.
Satu-satunya masalah adalah dia pemalu dan ketakutan banget. Dia hebat dalam situasi bisnis, tapi secara sosial, dia terus menghindar dan bersembunyi. Itu bikin gue kesel karena gue bahkan nggak bisa ajak dia ke acara makan malam formal karena dia bakal panik begitu keluar dari setelan jas dan pakai gaun malam.
Gue nemuin dia itu luar biasa, tapi Sam itu cewek gemuk yang tumbuh jadi anak gendut, pengalaman yang bikin rasa percaya dirinya nggak pernah bener-bener pulih. Gue berani taruhan sejuta dia masih per*wan. Dan jujur, itu bakal jadi taruhan yang paling aman yang pernah gue ambil. Di usia 25, gue nggak pernah lihat dia nge-date atau sama cowok atau cewek. Gue bisa tau dia punya perasaan tertentu sama gue: tatapannya yang berhenti agak lama, kaget tiba-tiba waktu gue ngomong, cara jarinya gemetaran dan gelisah waktu gue ngobrol sama dia.
Gue cowok yang lumayan ganteng: 193 cm, rambut hitam cokelat, badan atletis. Gue anggap penampilan gue ini alat buat kerjaan gue dan berusaha menjaga otot gue tetap terbentuk dan penampilan gue rapi. Biasanya gue pakai buat dapetin sumber daya dan memikat beberapa istri buat mempengaruhi suami mereka, tapi sekarang gue harus jadi umpan buat sekretaris gue. Gue bakal jadi umpan buat ngebuka dia dari cangkangnya sekali dan untuk selamanya dan buat mulai keluarga gue secepat mungkin.
Dengan rencana yang udah dibuat, gue mulai perlahan-lahan mengubah dan mengatur ulang janji temu sampai hari Jumat benar-benar kosong. Sam kayaknya nggak ngeh dan gue sendiri yang nelpon buat mastiin nggak ada orang bloon yang nelpon dia langsung dan ngerusak kerja keras gue. Gue nyewa penyelidik swasta buat ngikutin sekretaris kecil gue sementara gue riset sendiri dan belanja buat persiapan hari besar.
Seolah-olah bintang-bintang udah sejajar, semuanya berjalan lancar banget. Gue nerima laporan dari mata-mata pribadi dan tanggal yang gue pilih sempurna, semua yang gue pesan datang tepat waktu, dan Sam nggak curiga sama sekali. Jebakan udah dipasang dan dia bakal masuk dengan santai.
Dia masuk kerja hari Jumat itu dengan gaun bisnis merah yang cantik dan sweater. Senyum gugup khasnya dan anggukan kepala menyapa gue sebelum dia duduk dan nyalain komputernya. Dia natap layar dan ngeklik, lalu ngeklik lagi. Fakta bahwa nggak bakal ada siapa-siapa di kantor hari ini akhirnya kayaknya nyadar juga. Gue jalan dan berdiri di ambang pintu kantor pribadi gue.
"Sam, kayaknya kita bakal kesepian banget hari ini."
"Eh, Pak Smith, maaf. Kayaknya ada kesalahan jadwal di mana gitu. Saya bisa telpon beberapa klien buat mastiin mereka mau datang lebih awal.\" Suaranya keluar lirih, bikin gue nyengir.
"Nggak, nggak. Kita harus beresin beberapa hal di sini. Tapi, mau nggak kamu temenin saya minum teh?" Ada set meja bistro yang bagus di ruang santai yang biasa kita pakai buat kopi dan teh bareng.
"Oh? Boleh." Dia berdiri cepat. "Saya akan buat sekarang."
"Nggak, nggak... Nggak apa-apa kok. Saya yang buat hari ini. Duduk aja di sana." Gue ngedip ke dia dan dia ngegigit bibir bawahnya yang montok sebelum duduk di bistro.
Teh yang gue pesan rasanya ringan kayak yang gue tau dia suka, tapi ada rasa yang cukup buat nyembunyiin obat penenang yang gue tambahin ke infusnya. Itu bakal bikin dia pingsan dengan cepat tapi efeknya hilang dengan cepat, nyisain gue cukup waktu buat siapin dia. Gue taruh gelasnya di depannya dan duduk dengan gelas gue sendiri.
"Gue nggak tau deh gimana jadinya kalau nggak ada kamu, Sam."
Dia hampir keselek tehnya dan natap gue.
"Serius, Pak Smith?"
"Tentu saja. Gue anggap kamu bagian penting dalam hidup gue. Tapi, gue rasa kamu nggak dimanfaatin sepenuhnya di posisi kamu sekarang."
Mata dia berkedip sedikit lebih lambat dari biasanya saat dia terus menyeruput tehnya.
"Apa Bapak mau mecatin saya?"
"Nggak, nggak, nggak..." Gue tangkep gelasnya sebelum dia bisa ngejatuhinnya dan meluk pinggangnya dengan lengan gue yang lain, mengangkatnya bareng gue saat gue berdiri. "Malah, kamu harus mikirnya lebih ke promosi."
"Capek..." Matanya berkedip beberapa detik sebelum tertutup.
"Gue tau... gue tau."
Gue naruh gelasnya dan mengangkatnya ala pengantin, ngebawa dia ke kantor gue. Gue punya waktu sekitar 45 menit buat nyiapin semuanya. Gue udah bersihin meja gue, jadi gue taruh dia di bagian utama di depan kursi gue.
Sweaternya duluan, dibuang ke sofa di sudut gue, trus gaunnya gampang banget dibuka resletingnya dan ditarik lewat kepalanya. Nggak mungkin bisa turun lewat paha itu. Gue sempetin buat ngecap bibir gue ke daging lembut itu dan mengerang. Ini bakal seru.