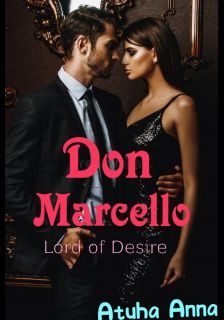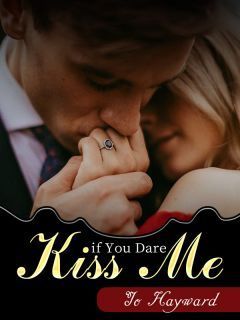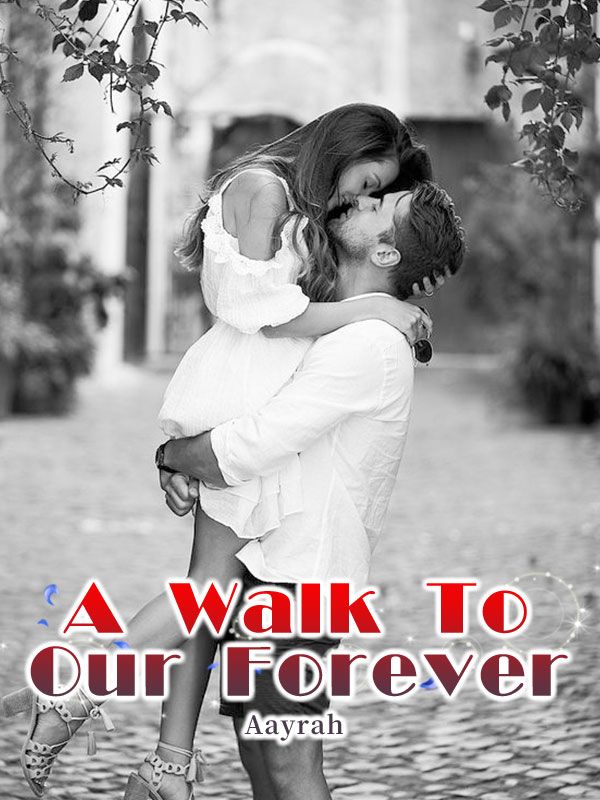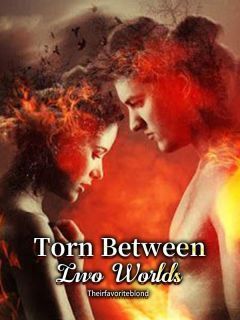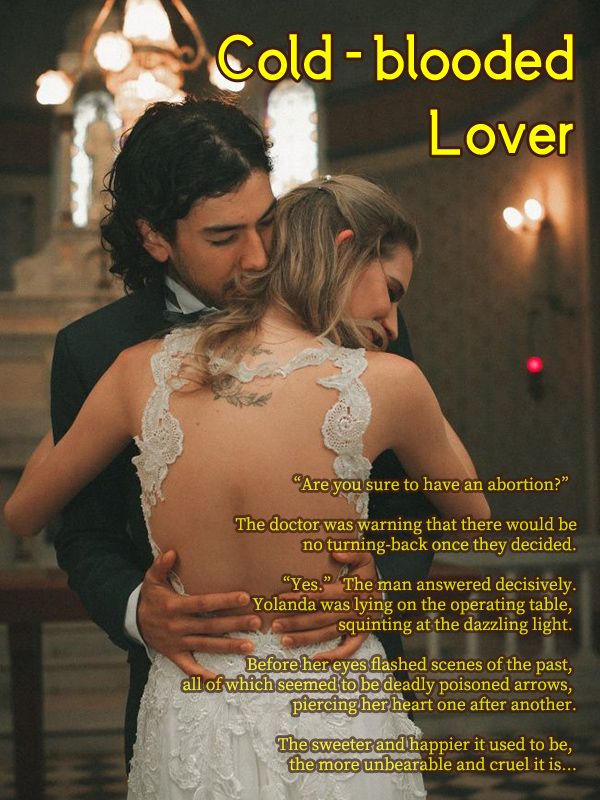Prolog
**Elsa De Luca**
Gue masih inget. Gue masih inget semuanya seakan baru kejadian tadi malem. Masih seger di pikiran gue; trauma yang bakal ngehantui pikiran gue selamanya...
"Jadi ini anak gue, **Elsa De Luca**," kata **Pastor** ke sekelompok rekan bisnisnya, narik gue lebih deket dengan sentuhan lembut. Gue senyum tipis, udah terlatih. Tumbuh di keluarga Mafia punya banyak untung ruginya, dan banyak aturan ketat yang harus dipatuhi, mulai dari lahir. Hal terpenting jadi cewek adalah gimana bersikap di depan orang-orang sekelas mereka.
Gue nyadar ini semua muka baru. Gue bahkan gak tau mereka di sini buat apa atau pesta ini tentang apa, tapi gue harus dateng karena **Papa** gue yang minta. Gue udah sering ngalamin ini, gue udah gak keras kepala buat nolak dateng karena gak pernah berhasil, soalnya **Papa** gue kan diktator dan dia selalu dapet yang dia mau.
Gampang sih kalau lo gak mikir terlalu banyak; bersikap anggun semaksimal mungkin, jangan kebanyakan senyum dan jangan terlalu cemberut, jangan nari kecuali **Mama** atau **Papa** lo ngijinin, jangan minum lebih dari dua gelas kalau minum minuman keras, kecuali lo yakin bodyguard lo deket dan lo gak bakal bikin malu diri sendiri di depan tamu dan ngerusak reputasi keluarga lo, jangan ngobrol sama cowok sembarangan, kecuali udah dikenalin sama **Papa** atau **Mama** lo, bla, bla, bla... Dan banyak banget aturan lain yang udah ada di ujung jari gue sejak kecil dan harus gue pastiin gak gue langgar kalau lagi di acara kayak gini.
"Wah, gimana kabarnya, **Elsa**? Kamu keliatan cantik banget malem ini," kata seorang kakek-kakek dengan seringai di wajahnya. Keliatan kayak kakek-kakek umur enam puluhan tapi punya pesona playboy.
Gue gak berani salting dan cuma ngegumam makasih.
"Dia udah ngambil gelar Sarjana Administrasi Bisnis di Columbia Business School. Gue berharap banyak dari dia," katanya dengan bangga ala ayah yang udah lama gak gue liat.
"Lo berhak banget. Dia keliatan pinter," komentar cowok botak pake jaket denim sambil minum bourbonnya.
"Iya, makanya gue berani nyekolahin dia sejauh itu," katanya.
Obrolan berlanjut beberapa menit sementara gue tetep senyum sopan dengerin omongan mereka.
Gue tau banget gimana orang Italia gak ngehargain potensi kerja cewek dan kemampuan mereka buat bangun kerajaan sendiri. Mereka lebih ngehargain cowok dan lebih percaya sama potensi mereka dibanding cewek. Untung atau sial, gue anak tunggal **Papa**, kecuali ada yang lain di luar sana yang gue gak tau. Gue gak percaya sama Mafia kalau soal anak cowok. Gak kebayang banget di seluruh dunia kalau **Papa** cuma mau gue sebagai anak tunggal dan pewaris utama, seorang cewek.
Setelah pamit, gue langsung ke toilet buat mastiin make-up gue masih bagus.
Gue narik napas panjang pas mau keluar dan berdoa semoga pesta ini cepet selesai. Gue bosen banget. Gak ada satupun yang gue kenal di sini selain **Papa** dan gue beneran gak bisa nikmatin diri gue.
Pas koridor nyambung ke aula utama rumah **Silvestri**, ada keributan yang bikin gue berhenti di tempat. Gue denger dua tembakan keras dari luar disusul teriakan cewek-cewek yang biasanya kenceng.
Ada apa sih?
Pelayan ngejatuhin nampan penuh gelas tequila, dan pecah berantakan di lantai. Cewek-cewek pada nangis kayak janda ditinggal mati dan semua orang lari ke sana kemari, cowok dan cewek gak bisa dibedain, semua mikirin diri sendiri.
Ada tembakan lagi.
Telinga gue langsung tuli sesaat dan gue berdiri di sana kayak kehipnotis, ngeliatin keributan, gak gerak sama sekali kayak gue gak ada di tempat ini. Orang-orang saling tubruk, ada cowok jatoh di lantai dan cewek-cewek terus aja nginjek dia sambil lari buat nyelamatin diri, ada yang nginjek badannya pake heels panjang mereka.
Badan berat jatoh nimpa gue bikin gue kaget dari lamunan. Gue jatoh langsung ke depan dan tangan gue kena pecahan kaca. Cowok itu lari ngelewatin gue tanpa nengok dan langsung ke pintu kayak yang lain.
Saat itulah gue sadar.
**Papa**!
Gue buru-buru berdiri dan lari ke pintu dengan marah.
**Papa**! Semoga **Papa** baik-baik aja, **Papa**!
Gue keluar rumah ke halaman depan tempat pestanya diatur. Banyak banget suara berisik; tangisan, mobil-mobil ngebut keluar dari jalan masuk, orang-orang lari kesana kemari dan semua pemandangan gak bisa dikenalin. Gue berusaha keras tapi susah banget buat nemuin **Papa** di antara semua cowok pake jas item di mana-mana.
Gue berdoa keras dalam hati semoga **Papa** baik-baik aja. Dia harusnya baik-baik aja. Ya Tuhan, tolong biarin dia baik-baik aja.
Gue nyoba nyelip di kerumunan dan ketabrak orang-orang yang lari buat nyelamatin diri, tapi itu gak ngebuat gue berhenti buat liat-liat.
Mungkin juga nyari gue. Pasti dia nyariin gue. Gak mungkin terjadi apa-apa sama dia. Bodyguard dia selalu siaga. Gue terus ngeyakinin diri sendiri padahal seluruh badan gue gemeteran dan gue hampir sepenuhnya ketakutan.
Ada kerumunan besar ngumpul di sisi kanan halaman, deket garasi. Gue lari ke arah mereka, nyoba nyelip tapi susah banget. Semua orang keliatan khawatir banget dan itu malah bikin gue makin tegang.
Gue berhasil nyampe ke tengah lingkaran tempat ketakutan terbesar gue jadi kenyataan. Gue gak kuat berdiri tegak. Kaki gue lemes, dan gue akhirnya duduk di tanah di samping **Papa** yang berlumuran darah. Sebelum gue sadar, air mata udah ngalir di pipi gue dan tubuh gue gemeteran hebat.
"**Elsa**," ada suara manggil gue dari belakang, dan tangan nyentuh bahu gue. Itu dia.
"Jangan berani-berani nyentuh gue!" gue teriak sambil ngehempas tangan dari bahu gue. Gue merangkak ke tempat **Papa** gue yang udah meninggal tergeletak di genangan darahnya.
"**Papa**," gue nangis, manggil, berharap dia bangun.
"**Papa**!" gue meluk dia, ngerangkul dia, bikin gaun abu-abu gue ikut basah kuyup kena darahnya, tapi itu gak penting buat gue saat ini.
"**Papa**, tolong bangun! Jangan pergi! Jangan tinggalin gue, **Papa**!" gue nangis, suara gue hancur dan gak berdaya. Gue meluk erat dia dan menjerit keras mohon dia jangan ninggalin gue.
"**Elsa**!" seseorang manggil gue dan beberapa tangan nyoba misahin gue dari **Papa**.
"Jauhin gue!" gue teriak, tiba-tiba benci sama semua orang di sekitar gue.
"**Elsa**, tenang ya," suara yang sama bersikeras. Gue langsung noleh buat ngeliat dia. **Matteo**, bodyguard **Papa** keliatan bersalah banget.
"Lo kemana aja? Lo di mana pas ini semua terjadi?" gue bener-bener teriak sekenceng-kencengnya.
"Nona **Elsa**, tolong coba tenang," katanya.
"Tenang? Berani-beraninya lo nyuruh gue tenang? Jauhin gue dan **Papa** gue!" gue berusaha keras tapi gak bisa ngejaga suara gue biar pelan. Perhatian semua orang udah ke arah gue dan gue bertingkah kayak orang kesurupan.
Gue balik lagi buat berduka dengan kepala gue ditaruh di dada **Papa**, ngerasain hidup yang hilang dari gue.
**Papa** tersayang gue udah pergi. Gue gak mau hidup tanpa dia. Gue punya banyak rencana bunuh diri yang muter di pikiran gue yang lagi kacau.
Gue harus tetap hidup!
Gue harus balas dendam!
Siapapun yang ngelakuin ini bakal bayar mahal nyawa mereka buat ini! Gue bersumpah atas jasad **Papa** gue.
Sirine ambulans bunyi dari belakang kerumunan, dan hal selanjutnya yang gue tau, gue ditarik paksa dari **Papa** gue. Gue nangis dan menjerit dengan getir. Saat itu gue udah kehilangan semua kendali diri dan akal sehat gue. Gue cuma bisa mikirin balas dendam; pembunuhan berdarah!