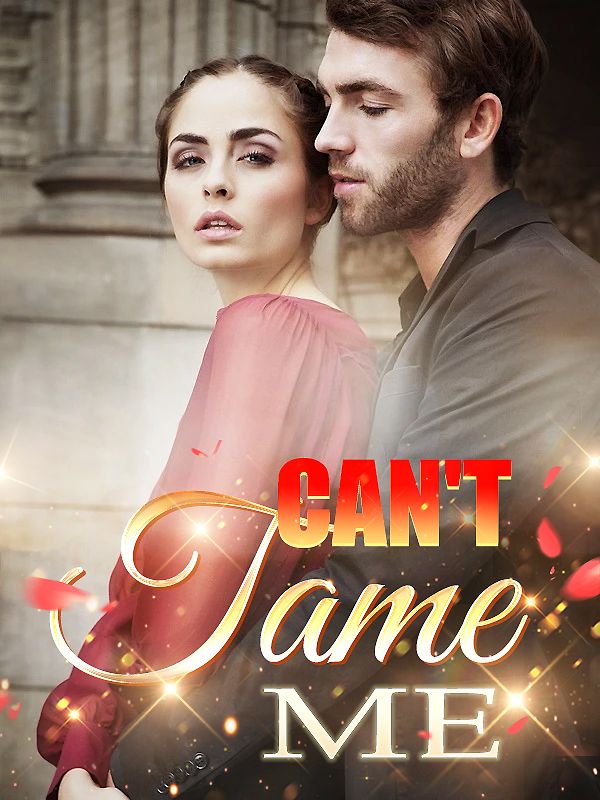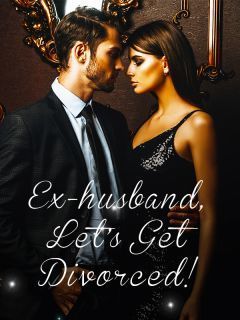“Lyra, buruan; pelanggan nunggu!” Gue rebut paket dari tangan Sekretaris yang bodoh ini biar bisa langsung ngacir naik sepeda. Gue kerja sebagai kurir di New York, dan si idiot ini bikin gue buang-buang waktu berharga gara-gara dia salah ngepak. Waktu itu duit, dan gue nggak punya banyak waktu buat dibuang-buang.
Gue udah nempuh lebih dari 1.000 kilometer hari ini, tapi gue pengen bisa ngejar dua atau tiga kali lagi biar gaji gue hari ini bisa naik. Demi capai target, gue ngebut di tengah macet, nyelip-nyelip di antara mobil, kadang-kadang nempel sama bus atau taksi buat nambah kecepatan.
Klien gue selanjutnya ada di tengah-tengah Manhattan. Gue harus ke gedung Veroni, di salah satu kawasan bisnis di Big Apple. Itu tempat yang nggak pernah gue injak, meski kerjaan gue begini, karena itu kayaknya markasnya para vampir, dan mereka biasanya nyuruh antek-anteknya buat urusan yang gue kerjain. Tapi, nggak masalah buat gue ke sana karena duit nggak berbau, nggak peduli ras, nggak peduli negara, dan darimana pun asalnya, gue terima tanpa malu.
Sambil merhatiin GPS pakai satu mata, gue liatin gedung-gedung di sekitar gue, mikir-mikir apa yang harus gue harapkan. Seingat gue, gue belum pernah ketemu sama manusia non-manusia, dan beda sama orang-orang yang gue temui, gue nggak pernah tertarik sama mereka. Untungnya, vampir itu paling berisiko, jadi meski gue tinggal di kawasan yang isinya cuma kaum gue, gue lumayan tahu tentang mereka.
Pertama-tama, gue tahu dulu ada masanya mereka ngeburu kaum gue buat dimakan, gue bersyukur banget dilindungi perjanjian utama. Itu perjanjian non-agresi yang ngelarang perburuan dan konsumsi individu lain tanpa izin.
Walaupun gue nggak pernah percaya sama keadilan atau hukum buat lindungin gue, bonus yang ditawarin perusahaan gue karena datang jauh-jauh dari kawasan gue, bikin gue nggak terlalu khawatir. Kalau ada yang nggak beres, biar nanti gue kasih tahu. Lagian, ini bukan pertama kalinya gue harus jaga diri sendiri.
Gue sandarin sepeda ke tembok, gue bilang ke diri sendiri, toh, semua manusia yang dua kaki itu sama aja, jadi gue nggak perlu takut sama mereka lebih dari yang lain. Sambil merhatiin gedung dengan jendela yang kinclong dan garis-garisnya yang bikin pusing, gue juga mikir kalau kebanyakan orang di dalemnya pasti peduli sama citra merek mereka. Makan tukang kirim barang mungkin ide yang buruk.
Gue benerin topi di kepala, gue selipin paket di bawah lengan sebelum masuk pintu otomatis dan jalan santai ke resepsionis, ngebuang semua pikiran buruk dari otak gue. Wanita di pintu masuk merhatiin gue datang dengan tatapan tajam, meringis ngelihat celana jeans gue yang sobek di lutut dan kaos Carapuce gue. Gue tahu banget gue udah lewat umur buat main Pokemon, tapi gue nggak peduli apa kata dunia.
Lagian, gue nggak ke sini buat fashion show. Nggak ngasih dia kesempatan buat komentar sedikit pun, gue langsung nyerang:
“Ada paket buat Tuan Veroni; gue harus naik ke atas; ini urgen!”
Dia ragu-ragu buat kasih gue akses ke lantai atas, cemberut jijik dan masih merhatiin gue. Dia mikir apa sih? Gue datang buat corat-coret di gedung ini?
“Ya udah, paling parah gue bisa tinggalin paketnya buat lo!” kata gue, sambil mengangkat bahu. Buat gue, nggak masalah; gue bilang, “Salah lo kalau pelanggan nggak dapat tepat waktu.”
Dia gigit bibir, khawatir, sibuk sama berkasnya, mikir untung ruginya, sementara gue pura-pura mau balik badan.
“Oke, oke! Dia akhirnya jawab dengan nada nggak enak.
Strategi kurir nomor satu: Kalau sambutannya nggak ramah, tunjukin ketenangan, terus sindir kalau orang yang diajak bicara berisiko kehilangan pekerjaannya. Ini salah satu teknik favorit gue. Gue suka banget ngelihat kepala departemen kecil berubah dari sombong jadi takut. Sambil senyum sinis, gue lihat dia nyodorin kartu tanda pengenal pakai ujung jarinya.
“Harus dikembaliin kalau mau keluar!” Dia nyembur ke gue, langsung balik badan ngadepin layar komputernya.
“Nggak usah kaget!” gue bilang dengan nada ketus. “Gue yang mimpi mau mulai koleksi!”
Gue pergi sementara dia ngasih gue tatapan sinis. Ujungnya nggak wajib, tapi gue tambahin biar seru.
Gue masuk pintu lift, dan ternyata kejepit di tengah-tengah sekumpulan pria dan wanita pakai setelan gelap yang serius, berpakaian rapi banget. Gue kira mereka kebanyakan pengisap darah, tapi gue nggak tahu siapa mereka, dan jauh di lubuk hati, gue nggak peduli. Gue cuma mikirin bayaran gue, dan sementara itu, gue nyelip ke pojok buat merhatiin mereka lebih baik.
Akhirnya, gue buru-buru ke kantor yang ditunjuk, ngetok pintu sebelum masuk tanpa nunggu jawaban. Lagian, makin cepet gue selesai, makin cepet gue keluar dari tempat yang bikin gue agak nggak nyaman ini.
Karena terburu-buru, gue berhadapan langsung sama pria tinggi berambut gelap pakai jas dan dasi, yang nggak sengaja gue tabrak.
Sambil ngomel-ngomel sama orang yang badannya kegedean, gue mundur selangkah; tapi, gue baru aja gerak, dia megang lengan gue.
“Aroma lo enak banget…” Dia bilang ke gue dengan suara melamun sementara lubang hidungnya melebar.
Gue kedip, bingung, mikir dia kayaknya nggak waras. Ngangkat alis, bingung, gue coba ngebebasin diri sambil ngejelasin apa yang gue lakuin di sini.
“Gue bawain paket buat Tuan Veroni!”
Dia nggak ngelepasin gue, matanya yang hitam merhatiin gue dengan niat mau masuk ke jiwa gue.
“Gue!” Dia bilang sambil senyum miring merekah di bibirnya. Kebetulan banget! Gue percaya kita ditakdirkan buat…
Gue potong jawabannya, yang gue rasa bakal berat banget, dengan neken paket ke dadanya dengan agak kasar sebelum nyodorin tablet buat tanda tangan.
“Tanda tangan di sini, ya!” jawab gue dingin, nyenggol dia biar ngelepas lengan gue, yang masih dia pegang erat. Begitu dia akhirnya mutusin buat ngelepas genggaman di pergelangan tangan gue, sambil reflek ngambil paket, gue tunjukin layarnya dan tempat buat tanda tangan. Apa pun yang terjadi, tetap profesional. Strategi nomor buat pengantar barang. Tekniknya biasanya berhasil buat rayuan tingkat rendah dan orang-orang kantoran yang nyebelin.
Sayangnya, kali ini itu bagian dari permainan karena dia natap gue tanpa gerak, seolah dia nunggu sesuatu selain paket, yang kayaknya sama sekali nggak bikin dia tertarik.
Matanya bersinar dengan kilauan yang nggak ngasih tahu gue apa pun yang berharga. Berharap biar cepet selesai, karena semua ketakutan gue kayaknya jadi kenyataan, gue lanjut berusaha buat tetap tenang meski rasa nggak nyaman tumbuh di dalem diri gue.
“Tuan Veroni, mau paketnya atau nggak?” gue tanya dengan mendesak.
Nggak disangka, suara laki-laki mengejek lain bergema agak jauh.
“Jadi, bos, feromon lo udah nggak mempan lagi?”
Gue condongin kepala ke depan biar bisa ngelihat lebih jelas di belakang klien tolol gue, nemuin seorang pria duduk di meja kenari besar yang natap kita sambil senyum. Dia tiba-tiba mendekat dengan gaya predator, yakin sama diri sendiri, seolah gue bakal meleleh di bawah pesonanya. Gue menyipitkan mata, merhatiin pria pirang tinggi dengan kulit pucat yang kontras banget sama setelan hitamnya.