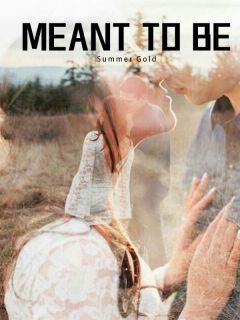Introduction
Table Of Contents
Introduction
Suami Elyana, Lukas Wilhems, membuatnya percaya bahwa dia yang bersalah atas kegagalan pernikahan mereka. Ketika dia ketahuan berciuman dengan wanita lain, Lukas menggunakan alasan bahwa istrinya tidak bisa memberinya anak, mendorong Elyana untuk mengajukan gugatan cerai untuk memutuskan hubungan sepenuhnya.
Dikhianati, terluka, dan disalahpahami, dia meninggalkan Inggris untuk selamanya. Dia menemukan perlindungan di sisi sahabatnya.
Karena selalu bersama siang dan malam, Elyana akhirnya merasakan jantungnya berdebar keras ketika dia dekat. Tapi bagaimana jika dia menemukan kebenaran di balik kebohongan mantan suaminya sebelum dia mengetahui apa yang sebenarnya dia rasakan?
Akankah rahasia itu mendorongnya untuk kembali ke Lukas, atau akankah itu menjadi katalis baginya untuk sepenuhnya menolaknya dan membiarkan hatinya melakukan apa yang dibisikkannya?
Read More
All Chapters
Table Of Contents
Bab 1
Bab 2
Bab 4
Bab 5
Bab 6
Bab 9
Bab 10
Bab 13
Bab 14
Bab 15
Bab 16
Bab 17
Bab 18
Bab 19
Bab 20
Bab 21
Bab 23
Bab 24
Bab 25
Bab 26
Bab 27
Bab 28
Bab 29
Bab 30
Bab 31.2
Bab 32
Bab 35
Bab 36
Bab 37
Bab 38
Bab 39
Bab 40
Bab 41
Bab 42
Bab 43
Bab 45
Bab 46
Bab 48.2
Bab 49
Bab 50
Bab 51
Bab 52
Bab 53.1
Bab 54.1
Bab 55.1
Bab 55.2
Bab 56
Bab 57
Bab 58
Bab 59
Bab 61
Bab 63
Bab 64
Bab 65
Bab 67
Bab 70
Bab 71
Bab 72
Bab 73
Bab 74
Bab 75
Bab 76
Bab 77
Bab 78
Bab 80
Bab 81
Bab 82.2
Bab 83
Bab 84.1
Bab 84.2
Bab 85
Bab 86
Bab 87.1
Bab 87.2
Bab 88
Bab 90
Bab 91
Bab 94
Bab 95
Bab 96
Bab 97
Bab 98
Bab 3
Bab 22
Bab 53.2
Bab 79
Bab 12
Bab 44
Bab 69
Bab 89
Bab 11
Bab 47
Bab 62
Bab 68
Bab 92
Bab 54.2
Bab 7
Bab 48.1
Bab 60
Bab 93
Bab 66
Bab 33
Bab 34
Bab 8
Bab 82.1
Bab 31