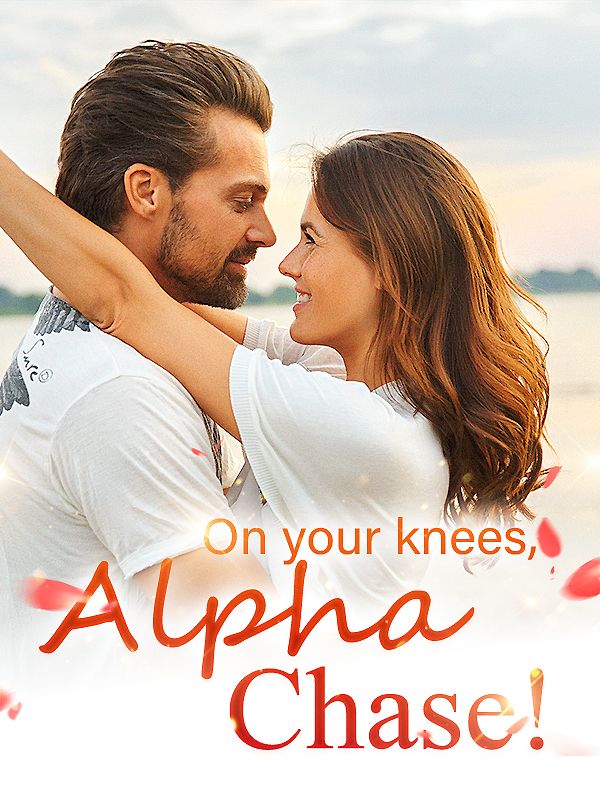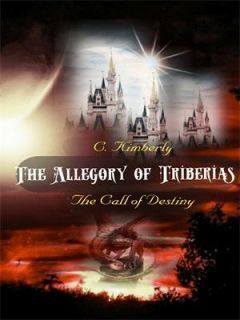Introduction
Table Of Contents
Introduction
Buku kedua dari seri 'Si Culun Bisa Bertarung'
*Kamu perlu membaca buku pertama untuk memahami yang satu ini*
Setelah Adam kehilangan ingatannya, Cassandra berjuang untuk menjaga jarak dalam upaya melindungi orang yang dia cintai.
Kali ini, dia tidak punya pilihan untuk tidak ikut dalam pertempuran berbahaya lagi. Demi orang-orang yang dia cintai, dia terpaksa membahayakan nyawanya sendiri, berjuang untuk mencapai puncak.
Cassandra selamat dari sekolah menengah, tetapi siapa yang mengatakan bahwa kisahnya berakhir di sana. Masalah menumpuk dan dia bertekad untuk mulai menyelesaikannya.
Ini adalah kisah seorang gadis yang berjuang melalui hidup dengan segala yang dia miliki ketika semua orang mencoba menjatuhkannya.
*Peringatan: Banyak kata-kata kasar. Baca dengan risiko Anda sendiri*
Read More
All Chapters
Table Of Contents
Bab 1
Bab 2
Bab 3
Bab 4
Bab 5
Bab 6
Bab 7
Bab 8
Bab 9
Bab 10
Bab 11
Bab 12
Bab 13
Bab 14
Bab 15
Bab 16
Bab 17
Bab 18
Bab 19
Bab 20
Bab 21
Bab 22
Bab 23
Bab 24
Bab 25
Bab 26
Bab 27
Bab 28
Bab 29
Bab 30
Bab 31
Bab 32
Bab 33
Bab 34
Bab 35
Bab 36
Bab 37
Bab 38
Bab 39
Bab 40
Bab 41
Bab 42
Bab 43
Bab 44
Bab 45
Bab 46
Bab 47
Bab 48
Bab 49
Bab 50
Bab 51
Bab 52
Bab 53
Bab 54
Bab 55
Bab 56
Bab 57
Bab 58
Bab 59
Bab 60
Bab 61
Bab 62
Bab 63
Bab 64
Bab 65
Bab 66
Bab 67
Bab 68
Bab 69
Bab 70
Bab 71
Bab 72
Bab 73
Bab 74
Bab 75
Bab 76
Bab 77
Bab 78
Bab 79
Bab 80
Bab 81
Bab 82
Bab 83
Bab 84
Bab 85
Bab 86
Bab 87
Bab 88
Bab 89
Bab 90
Bab 91
Bab 92
Bab 93
Bab 94
Bab 95
Bab 96
Bab 97
Bab 98